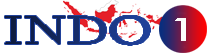Dengan jumlah penduduk yang sedikit, pendapatan per kapita Nauru mencapai USD 27.000 (setara dengan Rp 383 juta), lebih tinggi dari Amerika Serikat yang hanya USD 12.500 (setara dengan Rp 177 juta) pada saat itu.
Nauru pun menjadi negara terkaya di dunia.
Sayangnya, kekayaan Nauru tidak bertahan lama. Negara ini melakukan sejumlah kesalahan fatal yang membuatnya jatuh miskin dalam beberapa dekade.
Pertama, Nauru tidak mengelola pendapatannya dengan bijak dan cenderung boros.
Sebagian besar uang hasil penjualan fosfat dibelanjakan untuk konsumsi mewah dan proyek-proyek prestisius yang tidak produktif.
Misalnya, pemerintah Nauru membeli pesawat Boeing 737 untuk maskapai penerbangan milik negara bernama Air Nauru, padahal jumlah penumpangnya sangat sedikit.
Pemerintah juga membangun hotel bintang lima di pulau tersebut yang jarang dikunjungi wisatawan.
Selain itu, pemerintah juga menginvestasikan uangnya di berbagai bisnis dan properti di luar negeri yang ternyata banyak gagal atau bermasalah.
Kedua, Nauru tidak memperhatikan dampak lingkungan dari penambangan fosfat yang masif.
Penambangan ini telah merusak hampir 80 persen permukaan pulau, meninggalkan bekas-bekas lubang, batu kapur, dan debu yang tidak subur.
Tanah yang rusak ini tidak dapat digunakan untuk pertanian, perumahan, atau pariwisata.
Akibatnya, Nauru harus mengimpor hampir semua kebutuhan makanannya dari luar negeri.
Ketiga, Nauru tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi habisnya cadangan fosfat.
Fosfat adalah sumber pendapatan utama Nauru, tetapi sumber daya ini tidak dapat diperbarui.
Pada akhir tahun 1990-an, produksi fosfat Nauru menurun drastis karena cadangan fosfat yang tersisa sudah sulit diakses. Pada tahun 2006, penambangan fosfat di Nauru berhenti sama sekali.
Akibat dari kesalahan-kesalahan tersebut, Nauru mengalami krisis ekonomi yang parah.
Pendapatan per kapita Nauru anjlok menjadi USD 2.400 (setara dengan Rp 34 juta) pada tahun 2017, menjadikannya salah satu negara termiskin di dunia.
Nauru juga mengalami defisit anggaran, utang luar negeri, pengangguran, kemiskinan, dan ketergantungan bantuan asing.
Untuk keluar dari keterpurukan, Nauru mencoba berbagai upaya yang kontroversial dan tidak pasti.
Salah satunya adalah menjadikan negara ini sebagai tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka yang ditolak oleh Australia.
Sejak tahun 2001, Australia membayar Nauru untuk menampung ribuan orang dari berbagai negara seperti Afghanistan, Irak, Iran, Sri Lanka, dan Sudan yang mencoba masuk ke Australia secara ilegal melalui perahu.
Kebijakan ini menuai banyak kritik dari organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional karena dianggap melanggar konvensi pengungsi PBB dan merendahkan martabat manusia.
Banyak laporan yang menyebutkan bahwa kondisi di pusat penampungan Nauru sangat buruk dan tidak manusiawi.
Pengungsi dan pencari suaka mengalami kekerasan, pelecehan, penyiksaan, penyakit, depresi, dan bunuh diri.
Upaya lain yang dilakukan Nauru adalah menjual paspornya kepada warga asing yang ingin menghindari pajak atau hukum di negara asalnya.
Nauru juga menawarkan layanan perbankan offshore yang longgar dan tidak transparan kepada para pelaku kejahatan keuangan.
Kedua praktik ini membuat Nauru masuk dalam daftar hitam negara-negara surga pajak oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 2003.
Selain itu, Nauru juga berharap dapat mengembalikan industri fosfatnya dengan mengeksplorasi cadangan fosfat yang masih tersisa di dasar laut sekitar pulau.
Untuk itu, Nauru bekerja sama dengan perusahaan tambang asal Kanada bernama DeepGreen untuk menggali logam-logam penting seperti nikel, kobalt, dan mangan yang dibutuhkan untuk industri energi bersih.
Proyek ini diharapkan dapat mulai beroperasi pada tahun 2025.
Namun, semua upaya tersebut masih belum mampu mengembalikan kemakmuran Nauru seperti dulu.
Negara ini masih menghadapi banyak tantangan dan masalah, baik ekonomi maupun lingkungan.
Kisah Nauru menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.